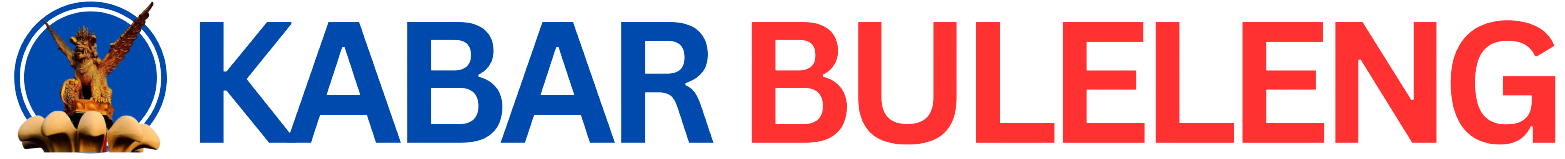Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memblokir rekening yang tidak aktif selama tiga bulan menuai beragam respons dari masyarakat. Di satu sisi, langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi negara untuk menutup celah pencucian uang dan pendanaan kejahatan. Di sisi lain, kebijakan ini menyisakan pertanyaan fundamental tentang proporsionalitas, keadilan administratif, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam sistem keuangan nasional.
Kebijakan ini pertama kali diumumkan secara terbuka oleh PPATK pada akhir Juli 2025. Ditegaskan bahwa rekening yang tidak melakukan transaksi selama lebih dari tiga bulan dapat diblokir sementara jika diduga berisiko tinggi, seperti terindikasi digunakan dalam transaksi judi online, penipuan, hingga perdagangan narkotika. Bahkan, lebih dari 28.000 rekening dilaporkan telah diblokir sepanjang tahun 2024.
Namun, yang menjadi masalah bukanlah niat PPATK memberantas kejahatan keuangan, melainkan cara pandang yang terlalu simplistik dalam menggeneralisasi bahwa rekening “tidak aktif” = mencurigakan. Dalam sistem perbankan, rekening pasif lazim ditemukan: ada nasabah yang menyimpan dana untuk tabungan darurat, rekening pelajar, hasil panen pertanian dan perikanan atau bahkan milik lansia yang tidak melakukan transaksi rutin. Apakah semua ini harus dicurigai sebagai pelaku pencucian uang?
Lebih problematis lagi, kebijakan ini mengaburkan garis batas antara pencegahan dan pelanggaran hak. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip praduga tak bersalah semestinya dijadikan fondasi utama. Pemblokiran rekening pribadi tanpa notifikasi atau proses klarifikasi di muka menandai adanya pergeseran dari pendekatan berbasis risiko ke arah tindakan administratif yang cenderung represif. Ini dapat mencederai asas due process dan perlindungan hak konstitusional warga atas properti dan akses keuangan.
Dari sisi teknis, kebijakan ini juga berpotensi menghadirkan kerumitan birokratis baru. Prosedur pembukaan blokir memerlukan nasabah untuk mengajukan permohonan ke bank terkait, yang kemudian diteruskan ke PPATK. Dalam praktiknya, proses ini bisa memakan waktu antara lima hingga dua puluh hari kerja. Hal ini tentu menyulitkan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, yang bisa jadi sangat bergantung pada akses rekening untuk kebutuhan sehari-hari.
Di sinilah letak kegentingannya: negara seolah sedang mendisiplinkan masyarakat melalui otoritas teknokratik, alih-alih membangun literasi keuangan dan sistem pengawasan berbasis edukasi. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, pendekatan ini justru bisa memicu ketakutan dan ketidakpercayaan, terutama jika tidak disertai transparansi dan ruang klarifikasi yang memadai.
PPATK seharusnya mengedepankan sistem analisis risiko yang lebih presisi — berbasis pola transaksi, jaringan penerima dan pengirim dana, serta metadata yang relevan — bukan sekadar menggunakan waktu dormansi sebagai indikator tunggal. Dalam era digital dan big data, pendekatan ini sangat mungkin dilakukan dan jauh lebih adil dibanding tindakan sweeping berbasis indikator kuantitatif yang seragam.
Selain itu, publikasi data agregat saja tidak cukup. PPATK dan otoritas terkait harus menjelaskan secara terbuka bagaimana parameter risiko ditetapkan, bagaimana sistem kecerdasan buatan mereka bekerja dalam menyaring rekening mencurigakan, dan sejauh mana perlindungan terhadap rekening sah diterapkan. Tanpa akuntabilitas ini, pemblokiran rekening bisa menjadi preseden buruk: bahwa negara dapat membatasi akses keuangan warganya tanpa dasar yang jelas dan dapat diverifikasi.
Di titik ini, kita harus mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam: apakah kita sedang menciptakan sistem keuangan yang tangguh dan inklusif, atau justru memperluas watak kontrol dan pengawasan negara atas urusan pribadi warga? Kebijakan ini menandai gejala awal dari otoritarianisme administratif, di mana niat baik dibungkus dalam logika teknokratis yang minim empati dan partisipasi publik.
Sudah saatnya PPATK dan regulator keuangan nasional merenungkan kembali arah kebijakan ini. Jika pemberantasan kejahatan finansial adalah tujuannya, maka yang dibutuhkan adalah sistem pengawasan berbasis keadilan, bukan penyeragaman administratif. Negara tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan satu arah — dari atas ke bawah — dalam urusan yang melibatkan hak akses ekonomi jutaan rakyat.
Sebaliknya, dibutuhkan pendekatan dua arah: pertama, memperbaiki sistem identifikasi risiko berbasis data dan konteks sosial; dan kedua, membuka kanal komunikasi serta pengaduan yang cepat dan adil bagi masyarakat yang terdampak.
Tanpa itu semua, kebijakan ini tidak lebih dari bentuk represi administratif yang disamarkan sebagai perlindungan publik. Dan dalam negara hukum yang demokratis, perlindungan hak warga seharusnya menjadi tujuan yang tidak bisa dinegosiasikan — bahkan oleh niat baik negara itu sendiri.
Oleh : Ahmad Iswanto., S.M.,M.M
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2021-2023